Kemarin telah aku katakan padamu, Amigos, bahwa sebuah dialog baru kemudian muncul menyertai pembacaan yang mana dari dialog itu lahirlah sebuah komunikasi yang hebat. Bukan sekadar dialog imajiner kukira, karena ia telah melibatkan cara berpikir hingga nampak dan memengaruhi suasana hati, melahirkan gagasan dan cara pandang baru untuk melihat dunia.
Juga telah kukatakan padamu bahwa perasaan bahagia itu bagaikan mengapung muncul dari dalam bumi kemudian berubah menjadi tiupan angin yang sepoi-sepoi, begitu sejuk mengelilingi. Memang ada kepuasan tertentu yang dirasakan seseorang dari pengalamannya menghadiahi diri sendiri dengan kesenangan. Dan aku pun merasa sangat puas ketika membaca cerpen-cerpen atau novel-novel yang sederhana dan membumi semacam karya-karya Leo Tolstoy, Nikolai Gogol dan Albert Camus, terutama The Stranger—ada yang menerjemahkan sebagai “The Outsider”, dalam Bahasa Indonesia juga ada dua versi “Orang Asing” dan “Sang Pemberontak”, bahkan ada terjemahan Bahasa Jawa-nya juga, “Wong Njobo”. Aku melihat bahwa karya-karya seperti itu begitu jujur, membumi dan begitu apa adanya. Tidak terlalu mewah dan luar biasa. Tidak mengawang-awang.
Kesederhanaan yang membumi dari sebuah karya yang dibuat oleh seniman, dan pemikiran-pemikiran mereka yang telah mereka coba sampaikan melalui karakter-karakter yang digambarkannya memang telah memberi aku kepuasaan tertentu, tetapi aku tidak mengatakan karya yang rumit dan mewah tidak memberiku hal ini juga. Karya-karya fantastis, magis, filosofis dan rumit YANG TIDAK TANGGUNG TANGGUNG pun bisa memberikan kesenangan. Sebagaimana One Hundred Years of solitude-nya Gabriel Garcia Marquez dan cerpen-cerpen karya Jorge Luis Borges. Karya-karya semacam itu memang menghibur dan memberiku kepuasan, bahkan memberikan sebuah kenikmatan yang sulit dilukiskan, hanya saja tidak selalu sukses mengajak diriku berdialog di sana. Aku hanya berdiri sebagai penonton, kadang perasaaku bisa terlibat, kadang tidak.
Sore ini, aku mendapatkan pengalaman baru lagi—sebuah pengalaman membaca yang mengasyikkan yang kembali kutemukan sebagaimana yang sudah aku sebutkan di tulisan sebelumnya. Sore ini aku membaca buku lama yang pernah aku tinggalkan karena aku tidak kuat membacanya, terlalu sedih, dan perasaanku tercabik-cabik ketika mengikuti kisah sepasang petani—Afanasii Ivanovich dan Pulcheria Ivanovna—yang semula memiliki kehidupan yang sangat bahagia di pelosok desa. Kehidupan yang tentram dan damai itu lalu seperti parasut yang bolong, tiba-tiba terjun bebas menuju titik nadir dan berantakan hanya dimulai dari ketika kucing pemalasnya tersesat dan setelah tiga hari kucing pemalas itu ditemukan dan dibawa pulang namun kini telah menjadi kucing yang asing dan liar. Aku terlalu melankolis ketika mengikuti kisah yang ditulis Nikolai Gogol yang berjudul “Petani-petani Ketinggalan Zaman” itu. Sebab baru pagi tadi aku menyelesaikan kisah itu—sudah sekitar 5 bulan sejak pertama kali aku membacanya.
Lalu sore ini, di buku yang sama oleh penulis yang sama—Nikolai Gogol—aku melanjutkan kisah berjudul “Jubah Panjang”.
Rasanya ada sesuatu kekuatan dari dalam bumi, aku tidak bisa menjelaskannya kenapa, tetapi aku bisa bersimpati dengan tokoh yang berada di dalamnya—Akakii Akakievich. Cerita itu tidak harus terlalu kejam dalam sebuah angan-angan. Tidak harus selalu heroik yang melakukan pekerjaan besar terhadap dunia. Tidak juga harus selalu berbunga-bunga dan puitik seperti yang selalu dikeluhkan oleh karakter yang bernama Batavus Droogstoppel, seorang makelar kopi—yang menceritakan dirinya sendiri dengan sudut pandang orang pertama—mengisahkan pertemuannya dengan teman lama; Max Havelaar. Ia kini adalah seorang pengusaha dan keterlibatannya dalam menerbitkan buku yang ditulis Max itu hanya demi alasan profit—katanya. Tetapi cerita-cerita seperti itu—“Jubah Panjang”-nya Nikolai Gogol—bisa membawaku pada sebuah arti hidup. Minimal membuka dimensi sebuah sudut pandang apa arti hidup bagi seseorang. Sebuah makna yang bisa membuatku melihat dunia dengan cara berbeda bahwa di suatu waktu dan zaman di bumi antah berantah,—meskipun aku tahu itu khayalan—ada dunia dari seorang yang miskin, yang hanya mendapatkan gaji 400 rubel setahun.
Apa artinya 400 rubel setahun pada tahun 1835—ya buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1835— di Rusia? Aku tidak mengerti, tetapi aku tahu ia begitu miskin.
Ia bertahan bertahun-tahun dengan jubuh jelek yang banyak tambalannya. Lalu pada suatu hari jubanya sudah tak mampu lagi ditambal, ia menderita dan tak punya uang untuk membeli sebuah jubah baru. Itu baru kisah pertengahan tetapi dari kiah itu aku jadi begitu mengerti satu hal—dari banyak hal yang bisa diambil dari kisah ini—, bahwa di St Petersbug orang bisa kapan saja mati kedinginan, bisa mati kelaparan, sementara di Indonesia, semuanya enak. Gak ada orang mati kok karena kedinginan. Mati karena kelaparan juga jarang-jarang.
Kisah-kisah seperti yang diceritakan Nikolai Gogol adalah kisah-kisah sebagaimana War and Peace nya Leo Tolstoy—aku belum selesai menamatkan buku ini, gak kuat baca e-book-nya, semoga di kesempatan berikutnya aku bisa membeli buku ini—atau cerita melalui Mersault-nya Albert Camus, seperti yang sudah kusebut di awal, begitu sederhana dan membumi. Tidak terlalu berangan-angan dan yang paling begitu terlihat tidak melulu mengesankan seorang karakter yang heroik.
Dialog-dialog baru juga melahirkan komunikasi ketika membaca Kolom demi Kolom-nya Mahbub Djunaidi. Sore ini, misalnya, aku membaca kolomnya yang berjdul “Mengecam PBB” yang terbit pada tanggal 5 November tahun 1977. Membaca judulnya saja, langsung timbul pertanyaan, “Ada apa?”. Aku tidak ingat dalam sejarah, sebenarnya ada masalah apa di tahun itu, tetapi aku mendapatkan sebuah kesan bahwa Pak Mahbub Djunaidi sedang memberikan pandangannya ketika PBB sedang ulang tahun ke 32. Lihatlah pembukaan kolom ini: Orang pertama—dan terakhir—yang menggedor mimbar PBB dengan sepatu pastilah Nikita Khruschcev. Dari penjelasan itu, aku seperti berkata, “Oh jadi ada masalah dengan PBB.” Tetapi kata Pak Mahbub, “Ini bukan seberapa. Walau tanpa buka sepatu dan menggedor mimbar. Bung Karno lebih sadis lagi di depan Sidang Umum ke-15 tanggal 30 September 1960.” Sebagaimana kita tahu akhirnya Indonesia keluar dari PBB pada waktu itu. Dengan gaya kocak Pak Mahbub seakan-akan melukiskan kalau Bung Karno berkata begini: “Komposisi Dewan Keamanan brengsek, mesti diritul, tidak mencerminkan kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh.” Pernyataan ini semakin jelas ketika Pak Mahbub kemudian menyisipkan pikirannya, “Kalau dipikir-pikir, sebetulnya gagasan mula kali mendirikan badan dunia ini berasal dari pemimpin-pemimpin negeri yang lagi kebingungan, terlunta-lunta dan bokek.”
Membaca buku-buku yang sederhana dan membumi macam Kolom demi Kolomnya Pak Mahbub ini membuatku mengerti bahwa di suatu zaman, ada suatu zaman tak kumengerti bagaimana pola kehidupannya. Sehingga mampu melahirkan komunikasi dari pertanyaan murni karena penasaran. Seperti sore yang lain, ketika Pak Mahbub ngomel-ngomel ala bapak-bapak soal listrik tahun 1975. Edan ya… tahun itu Pak Mahbub sudah ngomel-ngomel soal tarif listrik, sementara jaringan listrik baru masuk desaku saja tahun 1996. Bisa bayangkan kisah itu? Di dunia antah berantah di Jakarta, seseorang seperti Mahbub Djuanidi yang terkenal kritis, kocak dan tajam itu sudah mengkritik pemerintah bahwa PLN terlalu menarik tarif listrik yang begitu mahal, sampai-sampai sudah menyaingi Jepang, katanya. “Lah piye to ceritane?” tanyaku. Perlu diketahui biaya tarif listrik di Malaysia tidak ada apa-apanya, bahkan Taiwan hanya setengah dari tarif yang diminta dari Indonesia, berapa sih yang diminta? 22,00 rupiah per KWH. Ha! 22 rupiah per KWH? Bagaimana aku bisa membayangkan nominal itu di tahun 1975?
Demikian Saya Andy Riyan dari Desa Hujan. Sampai Jumpa.
Desa Hujan, 12 November 2020








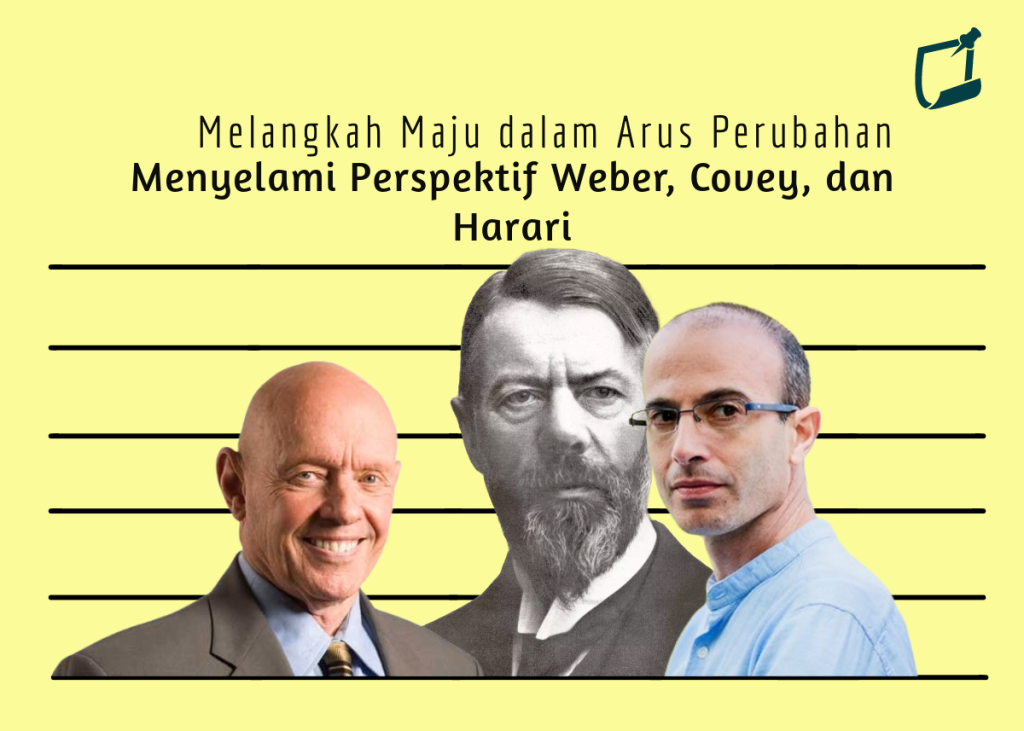


Katakan sesuatu/ Say something